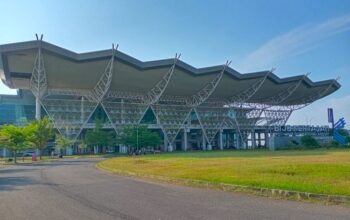Transformasi Kekuasaan di Era Digital: Power Morph dan Dampaknya pada Demokrasi
Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, bentuk kekuasaan politik mengalami transformasi signifikan. Yang dulunya bersandar pada institusi formal, konstitusi, dan prosedur rasional, kini berubah menjadi sebuah dinamika baru yang disebut sebagai “Power Morph”—sebuah istilhat untuk menggambarkan pergeseran kuasa digital dari struktur tradisional menuju jaringan afektif yang dibentuk oleh algoritme dan resonansi emosional.
Apa Itu Power Morph?
“Power Morph” merujuk pada perubahan mendasar dalam cara kekuasaan diperoleh dan dipertahankan. Kekuatan tidak lagi hanya lahir dari jabatan resmi atau lembaga negara, tetapi lebih kepada kemampuan menciptakan gema emosional yang menyebar cepat melalui platform digital. Ini adalah sintesis dari teori afektivitas politik dan algoritmisasi pengaruh publik.
Dalam ekosistem ini, kebenaran bukan lagi ditentukan oleh data, argumen logis, atau aturan hukum, melainkan oleh jumlah likes, retweet, dan view di media sosial. Emosi menjadi alat utama pembentuk opini publik, mengalahkan fakta objektif. Inilah era ketika jempol lebih berpengaruh daripada parlemen.
Fictocracy: Pemerintahan Berbasis Narasi Emosional
Akibat dari fenomena ini muncul apa yang disebut “fictocracy”, yaitu situasi di mana persepsi kolektif dibentuk oleh narasi emosional yang seringkali jauh dari data empiris. Tokoh-tokoh politik membangun citra mereka tidak dengan program kerja, tetapi dengan menyentuh perasaan publik melalui simbol, cerita, dan momen-momen dramatis.
Contohnya bisa dilihat dari bagaimana figur seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Dedi Mulyadi viral di media sosial. Bukan karena program pemerintahannya, tetapi karena cuplikan pidato yang menyentuh, blusukan yang dikemas secara emosional, atau bahkan adegan tangisan yang terekam dalam video pendek. Di tingkat global, Donald Trump juga merupakan contoh nyata bagaimana resonansi emosional dapat mengalahkan validitas data.
Nodicentrism: Simpul Digital Sebagai Pusat Kekuasaan Baru
Selain itu, kekuasaan juga bergeser ke ranah digital. Platform seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan X (dulu Twitter) menjadi simpul-simpul kontrol yang lebih dominan daripada lembaga-lembaga negara. Fenomena ini saya sebut sebagai “nodicentrism”, yaitu situasi ketika node digital menjadi pusat kendali kekuasaan.
Platform-platform tersebut memiliki algoritma yang mampu membungkam suara kritis melalui praktik seperti shadow banning atau sebaliknya, meningkatkan visibilitas konten tertentu melalui boosting. Mereka pun ikut menentukan bagaimana suatu peristiwa dipahami publik melalui content framing. Ini adalah bentuk baru dari kontrol politik yang tidak terlihat namun sangat efektif.
Affective Simulation: Politik sebagai Pertunjukan Emosi
Kekuasaan di era digital juga semakin identik dengan penciptaan emosi buatan yang dirancang sedemikian rupa agar mudah menyebar. Saya menyebutnya sebagai “affective simulation”, yaitu produksi emosi melalui performa digital—menggunakan ekspresi wajah, narasi, musik, hingga visual yang mampu menciptakan resonansi luas.
Politikus yang minim program cenderung memperlihatkan sisi empatik mereka untuk mendapatkan simpati. Mereka bukan lagi penyusun kebijakan, melainkan penari emosi publik (choreographers of affects) yang mengatur suasana hati masyarakat. Contoh nyata bisa kita lihat dari gaya komunikasi Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil, atau tokoh Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang menggunakan narasi emosional untuk memobilisasi dukungan global.
Urgensi Kesadaran Naratif
Menghadapi semua ini, penting bagi kita untuk memiliki kesadaran naratif. Setiap video, meme, atau unggahan di media sosial bukanlah sekadar hiburan; mereka adalah bagian dari pertarungan makna sosial. Perlawanan terhadap kekuasaan yang bersifat afektif harus dimulai dari pemahaman akan simulasi emosi, bukan hanya sekadar informasi faktual.
Jika ingin menyelamatkan demokrasi, kita perlu membangun ulang struktur kekuasaan agar tidak hanya berbasis pada prosedur formal, tetapi juga pada narasi yang etis dan emosi yang sehat. Kita tidak bisa menghilangkan kekuasaan digital, tetapi kita bisa menjinakkannya jika mampu memahami mekanisme kerjanya.
Kita sebagai publik harus peka dalam membaca emosi kolektif dan bertindak sebagai penjaga narasi yang bertanggung jawab. Hanya dengan itu, kita bisa menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya informatif, tetapi juga manusiawi dan adil.